Aliran sungai yang membelah Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi, berwarna coklat pekat dan terbelah-belah. Terhampar tumpukan batu dan pasir menjadi bukit-bukit kecil. Dulunya ini sawah. Setelah lebih dari satu dekade beroperasi, para pemodal pertambangan emas tanpa izin (PETI) mengubah sawah itu menjadi area pertambangan.
“Saya sepuluh tahun menolak tambang emas. Tapi ada pemodal besar, orang terpandang di kampung berani melangkahi hukum adat. Orang ini menambang pakai alat berat. Aliran sungai pun diputus dan dialihkan,” kata Uncu melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/2024) waktu lalu.
Uncu—nama sebenarnya perlu disembunyikan karena alasan keamanan—adalah warga Pangkalan Jambu yang prihatin dan pernah mencoba melawan kehadiran PETI di kampungnya.
Uncu menceritakan, akibat pengalihan aliran Sungai Pangkalan Jambu, sawah-sawah petani kekeringan. Produksi padi turun drastis, membuat pendapatan petani tergerus. Akhirnya sebagian besar warga Pangkalan Jambu, yang rata-rata petani sawah, kepincut untuk menambang emas.
Bujuk rayu pemodal dengan iming-iming hidup sukses, dengan cepat membuat orang-orang di Pangkalan Jambu meninggalkan tradisi bersawah, beralih menjadi penambang emas ilegal.
Diketahui, penambangan emas ilegal mengakibatkan hampir setiap tahun daerah ini mengalami banjir. Pada 2015 lalu, banjir telah menewaskan seorang warga Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu.
Pertambangan emas ilegal di kawasan itu juga telah merusak sumber air bersih. Masyarakat kini terpaksa membeli galon air untuk mencukupi kebutuhan air.
Padi Merkuri dari Pangkalan Jambu
Tidak hanya itu, pertambangan emas yang masif di kawasan itu telah menghilangkan sekitar 600 hektare sawah. Angka tersebut berkontribusi signifikan terhadap turunnya produksi padi di Kabupaten Merangin, yang secara total sudah kehilangan 3.920 hektare sawah akibat PETI di 12 kecamatan. Alih fungsi lahan sawah itu mengancam ketahanan pangan, di tengah pasokan beras di Jambi yang bertahun-tahun selalu mengalami defisit lebih dari 40 persen.
Kebutuhan beras di Jambi dengan jumlah penduduk sekitar 3.677.678 jiwa sebanyak 89,7 kilogram/kapita/tahun atau sekitar 329.888 ton. Sedangkan produksi gabah kering giling (GKG) tahun lalu hanya 274.557 ton, yang apabila dikonversi ke beras sekitar 178.462 ton.
Dampak lainnya akibat PETI tak terlihat, tapi tak kurang berbahaya. Lebih dari satu dekade penambangan emas berlangsung, merkuri yang terlepas saat aktivitas penambangan sudah tak terhitung yang masuk ke sungai.
Dosen Universitas Jambi, Ngatijo memaparkan risetnya terkait merkuri di Sungai Batanghari. Penelitiannya memperlihatkan kandungan merkuri di sungai itu sudah melebihi ambang batas.
Merkuri di air sungai memang berfluktuasi pada kisaran <0,0005-0,0645 mg/L sedangkan pada sedimen sungai terdeteksi dengan kisaran 0,01-0,42 mh/kg. “Sangat berbahaya bagi makhluk hidup,” kata Ngatijo. Mengutip Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004, ambang batas kadar merkuri di air dan laut adalah 0,001 ppm.
Sungai yang tercemar merkuri ini, ujar Ngatijo, jadi ancaman bagi jutaan orang di Jambi. Sebut saja nelayan yang menangkap ikan, konsumen perusahaan daerah air minum (PDAM), serta para petani yang menggantungkan sumber air irigasinya ke Sungai Batanghari.
Ada yang lebih mengkhawatirkan Ngatijo. Ia menyatakan, ada tren para petani kembali menanam padi lantaran tanahnya sudah tak menghasilkan emas. Keinginan warga ini telah didukung pemerintah. Padahal, kata dia, hasil penelitiannya pada 2018 lalu di Desa Sungai Jering, Kecamatan pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi menemukan kandungan merkuri dalam tanah bekas tambang di lahan sawah sebesar 0,00154-0,00501 ppm. Artinya, tanah bekas tambang juga tercemar merkuri di atas ambang batas aman.
Ini buruk bagi padi, karena secara alami tanaman ini memiliki daya serap yang tinggi terhadap merkuri. Ngatijo membuktikannya dengan menanam padi. Hasilnya, padi yang ditanam menghasilkan merkuri di atas ambang batas. “Kandungan merkuri dalam beras dari lahan bekas tambang disarankan tidak dikonsumsi karena membuat manusia cacat. Bahkan cemaran merkuri dapat menurun ke anak secara genetik,” ujarnya.
Dia menyarankan, sebelum sawah bekas tambang ditanam padi kembali, sawah itu harus diberi perlakuan memakai penyerap merkuri, yaitu media adsorben yang terbuat dari sekam padi. Hasil penelitian Ngatijo menunjukkan adsorben dapat menyerap merkuri hingga 43,36 persen dari tanah bekas tambang.
Dari Tambang Emas ke Tambang Pasir
Selain ada yang kembali menanam padi, banyak pula warga yang banting setir menjual pasir bekas tambang emas ilegal ke pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kebetulan, sekitar 30 kilometer dari Pangkalan Jambu, sedang dibangun PLTA Batang Merangin. PLTA ini dibangun PT Kerinci Merangin Hindro (KMH).
KMH adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga air milik mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Pembangunan megaproyek ini menerima pendanaan hijau dari bank plat merah sebesar USD 698,75 juta atau setara Rp9,8 triliun.
Proyek energi bersih tenaga air ini akan menghasilkan listrik 350 megawatt. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah meneken perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dengan perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla itu, pada 2018 lalu.

Menurut perjanjian itu, kepada PLN, PT KMH hanya menyuplai setrum selama lima jam pada saat beban puncak, yakni mulai pukul 18.00-23.00 WIB. Dengan begitu, kekurangan kebutuhan listrik PLN tetap disuplai energi kotor, batubara.
Direktur Utama KMH adalah Achmad Kalla, putera dari Jusuf Kalla. Selama beberapa tahun terakhir, Juduf Kalla juga terlihat sering berkunjung ke Jambi, didampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dan Bupati Kerinci, Adi Rozal.
Kembali ke cerita pasir. KMH ini membutuhkan banyak pasir karena harus membuat bendungan setinggi 120 meter dan menggali terowongan bawah tanah sekitar 11,6 kilometer. Perusahaan ini membutuhkan pasokan pasir dan batu yang besar untuk pembangunan tersebut. “Kalau sekarang emas sudah susah dicari. Tersisa batu dan pasir yang ditumpuk-tumpuk di lahan bekas sawah. Daripada tidak bisa dimanfaatkan, maka mereka jual ke Perusahaan (KMH),” kata Uncu.
Ia menyebut di Pangkalan Jambu beroperasi beberapa perusahaan cukup besar yang memasok pasir ke KMH. Dari dokumen penimbangan pasir KMH tahun 2023 yang diperoleh redaksi, salah satu perusahaan di Pangkalan Jambu itu diduga adalah PT Djoeng Jaya Perkasa. Perusahaan ini berbasis di Bangko dan beroperasi di Desa Sungai Jering. Namun, saat ini perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi karena tidak memiliki kontrak dengan PLTA.
“Sekarang warga sudah punya perusahaan sendiri. Sudah ada izin untuk memasukkan batu ke PLTA,” kata Uncu.
Menurut Uncu, di masa kejayaannya, pada tahun 2023, dari Pangkalan Jambu ini diduga pernah mengalir ribuan ton pasir dalam sehari. Satu perusahaan bisa mengirim sampai 1400 ton pasir per hari. Kala itu, KMH memang tengah meninggikan bendungan yang menghadang aliran Sungai Batang Merangin.
Tahun ini, sumber Merdeka.com mengatakan ada dua perusahaan yang memiliki kontrak memasok pasir ke PLTA. Satu pemain berada di Sungai Manau, dan satunya berada di Pangkalan Jambu atau Perentak.
Pembatasan pasokan yang dilakukan PLTA membuat perusahaan di Perentak hanya bisa mengirim 2.000 ton pasir setiap dua minggu. Dari jumlah itu, dalam satu ton, perusahaan ini dapat mengantongi Rp320 juta. Artinya dalam sebulan bisa menghasilkan Rp640 juta.
Menurut sumber, pembatasan pasokan diduga karena pekerjaan pembangunan bendungan dan terowongan sudah hampir selesai. Bersebab hal itu, perusahaan milik warga asli Perentak ini, kata Uncu, hanya memasok 15-30 truk setiap hari, masing-masing dengan bobot sekitar 14 ton, dari tambang emas ilegal atau sekitar 210-420 ton. Jumlah ini turun hingga 70 persen dari tahun sebelumnya.
“Kalau tahun lalu itu bisa antar 100 truk sehari. Sekarang sudah susah, paling banyak itu 30 truk. Kami juga tidak tahu kenapa kok dikurangi, mungkin pembangunan sudah mau selesai ya,” katanya.
Sementara itu, SK, seorang pekerja PT KMH, membenarkan permintaan pasir sudah sedikit, karena kebutuhan terhadap pasir memang tidak setinggi tahun lalu.
“PLTA tidak ambil pasir dari Perentak (Pangkalan Jambu) setiap hari libur (Sabtu-Minggu). Jadi setiap hari kerja mereka pasti antar,” kata pekerja PLTA itu mengungkapkan jadwal pengambilan pasir saat ditemui Merdeka.com di lokasi, Minggu (21/1/2024).
Humas PT KMH Aslori Ilham membenarkan material pembangunan PLTA disuplai oleh dua perusahaan di Perentak dan Sungai Manau.
“Perusahaan dari Perentak itu memang memasukkan bahan baku pasir ke PLTA. Kami juga membeli bahan baku sesuai dengan titik koordinat, Kami hanya membeli pasir,” katanya, saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com pada Kamis (07/03/2024).
Menurut dia, pihak perusahaan membeli bahan baku pasir dari Perentak tersebut ada IUP dan titik koordinat dari perusahaan.
Aslori menambahkan, selain itu ada juga perusahaan di Sungai Manau yang memasok bahan baku untuk pembangunan PLTA. “Tapi untuk saat ini tidak banyak lagi dikarenakan pembangunan hampir selesai,” ujarnya.
Aslori tak ingat berapa pasir yang masuk dalam satu hari ke KMH. Namun untuk satu bulan mencapai 1000 ton, atau dalam dua minggu sekali 500 ton. “Itu tergantung kebutuhan pembangunan PLTA,” ujarnya.
Kalau dulu, ujarnya, banyak pasir yang dibutuhkan. Asalnya tak hanya dari Perentak saja, ada juga dari Tapan, Siulak. “Kita juga tahu bahwa dari Perentak itu banyak tidak memiliki izin. Karena itu, untuk salah satu Perusahaan itu, kata Aslori, pihak perusahaan sudah memutus kontrak.
PETI Hancurkan Ekologi
Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf mengatakan penambangan emas yang mengeruk alur sungai, sempadan sungai, dan menghilangkan tutupan hutan di atasnya jelas sangat berbahaya secara ekologi. Tindakan ini menimbulkan bencana banjir dan longsor. Daerah-daerah yang dulunya tidak mengalami banjir parah, sekarang sangat mudah mengalami banjir.
Sedimentasi karena penambangan emas membuat sungai dangkal. KKI Warsi mencatat pada tahun 2021 ada 20 kali banjir di Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi, Sarolangun dan Kerinci. Bencana hidrologi ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 6.265 rumah terendam, 635 hektare lahan terendam.
Hasil pemetaan KKI Warsi melalui analisis citra satelit, setiap tahun area penambangan emas di Desa Raden Anom terus meningkat. Lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan ini mencatat pada 2017 lalu, angkanya berada di 150 ha, tahun berikutnya tak terdeteksi, lalu muncul kembali pada 2019 dengan luas 256 ha. Kemudian naik menjadi 283 ha pada 2020 dan melandai pada 2021 yang berada pada kisaran 269 ha.
Rudi menuturkan penambangan emas setiap dekade mengalami peningkatan teknologi. Dengan demikian daya rusaknya sangat masif. Awalnya, penambangan emas dilakukan secara tradisional, dengan mendulang di pinggir sungai. Namun sejak tahun 2000-an, penambangan emas menggunakan mesin dompeng.
Alat itu mampu menghisap sedimen sungai dan membawanya ke saringan khusus. Di tempat ini, pasir, kerikil dan lumpur akan terpisah dengan butiran emas dengan bantuan merkuri.
Saat alat ini booming, ada ratusan dompeng yang berada di sepanjang Sungai Batanghari. Perlahan air menjadi keruh. Setelah emas di alur sungai mulai habis, para penambang emas kembali berinovasi. Area penambangan tidak lagi berada di sungai utama, melainkan merambah anak-anak sungai menggunakan alat berat.
“Semakin meluas, tidak hanya sungai melainkan sawah, kebun karet, ladang bahkan hutan lindung,” kata Rudi.
Ia mengatakan KKI Warsi juga mencatat setiap tahun area penambangan emas ilegal semakin meluas. Pada 2016 penambangan emas seluas illegal ini tercatat 10.926 hektar di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Kemudian tahun 2017 naik drastis menjadi menjadi 27.535 di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo.
Luasan area itu melonjak jadi 33.832 ha pada 2019 di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo dan Tebo. Pada tahun 2020 mencapai 39.557 ha dan pada 2021, wilayah tambang ilegal sudah mencapai 42.362 ha.
“Perluasan area tambang ilegal itu mencapai 288 persen pada 2021 jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016,” ujar Rudi.
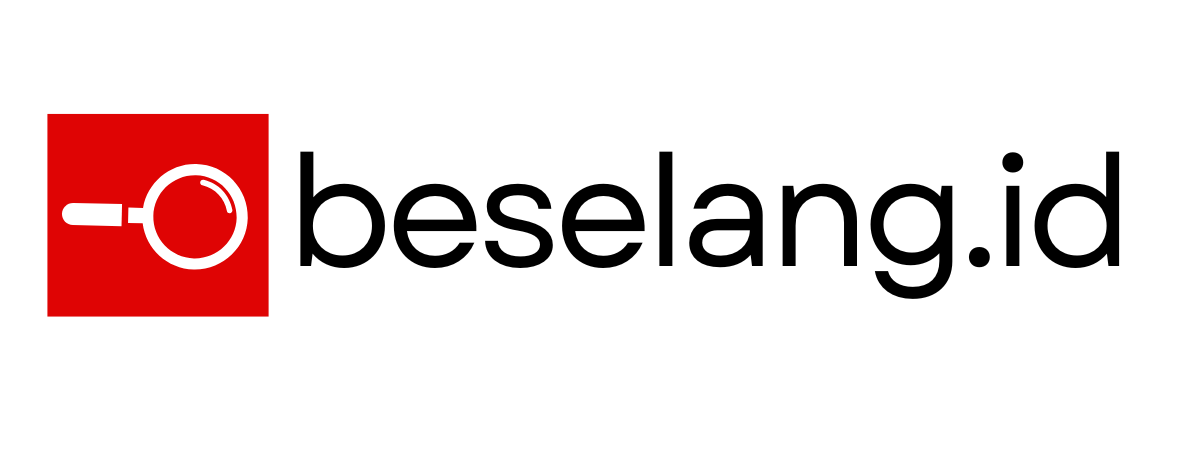







Leave feedback about this