Empat perempuan menyanyi dan menari di depan layar panggung yang menyala. Lampu berkilau serasi dengan dentuman musik. Ribuan penonton histeris, mandi cahaya dan memainkan tongkat yang berpendar-pendar.
Malam berhias cahaya merah muda ini adalah konser Black Pink di jantung kota Seoul, Korea Selatan setahun silam, akhir dari tur Born Pink. Walau menelan setrum yang besar, konser bintang KPOP diklaim ramah lingkungan. Sebab Negara Korea Selatan telah berkomitmen menggunakan energi bersih.
Bentuk nyata komitmen Korea mendapat respons positif dunia. Sehingga Black Pink terpilih sebagai duta UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Inggris. Penghibur dengan nama penggemar Blink menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, atas keberhasilan mereka membuat video kampanye untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam mengatasi perubahan iklim.
Penghormatan dunia pada negeri gingseng terkait penggunaan energi bersih tak seutuhnya sempurna. Untuk mencukupi kebutuhan energi, Korea Selatan mengimpor pelet kayu dari Jambi, Indonesia. Dan bahan bakunya, ada dari deforestasi dan pembalakan liar.
“Kayu tanpa surat, masuknya tengah malam. Ya harus dikawal petugas biar aman untuk masuk ke sini,” kata MH, pekerja sawmill di Jambi, Rabu (28/8/2024).
Sawmill belum mengantongi izin, sambung MH namun sudah bertahun tahun beroperasi. Semenjak aturan ketat banyak sawmill di Jambi yang tumbang. Namun sawmill tempat MH bekerja tak kekurangan bahan baku.
Ada pasokan kayu hasil pembalakan liar kawasan hutan seperti di Sarolangun dan Muaro Jambi, perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Kemudian kayu-kayu dari kebun masyarakat.
Limbah produksi berbentuk seberan menumpuk di sawmill. Kebetulan perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL) memborong potongan kayu yang tak terpakai. “Mereka sekali ambil satu truk lah sekitar 6-7 ton,” kata MH.
Meskipun menjual seberan ke RPSL, MH mengaku tak berhubungan langsung, melainkan ada peran pihak ketiga. Mereka ini kaki tangan perusahaan yang mengumpulkan seberan-seberan dari belasan sawmill di wilayah ini, kata MH.
Energi dari deforestasi
RPSL yang disebut MH adalah perusahaan di bidang energi ‘bersih’ mendukung transisi energi pemerintah. Dalam dokumen analisis dampak lingkungan milik PT RPSL; perusahaan tersebut memproduksi 2×15 Megawatt pembangkit listrik dari tenaga biomassa. Dari kapasitas produksi setrum tersebut dialirkan ke PLN sebesar 2×10. Sisanya yakni 2×5 megawatt untuk kebutuhan sendiri.
Selain itu, anak perusahaan Weal Union Limited dari Hongkong, juga memproduksi pelet kayu sebanyak 288 metrik ton per hari. Dengan kapasitas produksi sebanyak itu, maka RPSL minimal membutuhkan bahan baku sebanyak 104.400 ton setiap tahun.
Tidak hanya dari sawmill, kayu-kayu juga berasal dari petani-petani yang menebang kebun karet untuk diganti tanaman sawit. Setiap harinya ada puluhan truk mengantar kayu racuk atau kualitas rendah dan karet ke RPSL.
“Kami mengantar kayu racuk ke RPSL untuk dijual,” kata TN, sopir truk dari Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi.
Dalam truk dengan bobot muatan delapan ton, sambung TN selain karet, ada banyak jenis kayu lain yang berkualitas rendah dan tidak seperti meranti atau tembesu yang kualitas ekspor.
Lelaki yang sudah belasan tahun menjadi sopir angkutan kayu, menuturkan rata-rata kayu dibawa dari perkebunan karet milik petani. Namun ada juga dari luar kebun karet.
Bahan baku kayu RPSL tidak hanya dari perkebunan karet, kata Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, lembaga konservasi yang fokus pada isu deforestasi dan kejahatan lingkungan.
Feri menyebut untuk menghidupkan pembangkit biomassa dan produksi pelet kayu, RPSL membutuhkan minimal 104.400 ton bahan baku.
Kebutuhan tersebut tertuang dalam dokumen amdal perusahaan. Sementara RPSL tidak memiliki izin tanaman hutan industri (HTI). Untuk memenuhi kebutuhan, perusahaan membeli limbah pabrik olahan kayu (sawmill). Kayu mereka diduga berasal dari pembalakan liar Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) dan hutan penyangga di sekitarnya.
Kayu yang masuk ke sawmill di Jambi berkualitas tinggi. Namun tidak semua bisa digunakan. Sehingga limbah kayu dengan kualitas rendah (seberan) dan serbuk kayu diborong RPSL. “Memang limbah, tapi kayunya ilegal dari perambah,” kata Feri.
Kebutuhan kayu dari sawmill cukup tinggi, kata Feri sesuai dengan data dokumen amdal RPSL. Mereka menggunakan bahan baku beragam untuk produksi setrum biomassa dan pelet kayu pada 2017 lalu seperti cangkang sawit 281,9 ton, fiber sawit sebanyak 59.967,5 ton, kayu karet 32,206,2 ton, kayu seberan 371 ton dan serbuk kayu sebesar 2.090,6 ton.
Berdasarkan data tersebut Feri menyebut bahan baku terbesar dari fiber sawit. Hasil penelusuran Perkumpulan Hijau sumbernya dari 16 perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut ada dalam kawasan hutan dan sisanya banyak pula yang berada di kawasan lindung gambut.
Meskipun RPSL tidak secara langsung melakukan deforestasi, namun bahan baku produksi biomassa dan pelet kayu mereka, berasal dari perusahaan yang melakukan deforestasi. Bahkan sejumlah perusahaan tercatat mengalami kebakaran berulang.

Sementara izin penebangan kayu karet RPSL hanya empat desa yaitu Air Hitam, Kebon Sembilan, Talang Belido dan Petaling. Lokasi ini sudah sesak tanaman sawit. Artinya kebutuhan kayu mereka dari luar lokasi izin.
“Sudah sulit cari tebangan kebun karet di Jambi. Mereka juga tebang kayu rengas dan bungur. Padahal pohon ini pelindung sepandan sungai,” kata Feri.
Kerugian Negara
Jika RPSL menerima tebangan kayu rengas dan bungur, tentu kebanyakan sungai di Jambi akan gundul. Hal ini mengancam ekosistem sungai, karena akan menyebabkan sendimentasi dan erosi.
Dalam dokumen amdal perusahaan, kayu bungur dan rengas menjadi bahan baku untuk memproduksi 288 ton per hari pelet kayu. Namun tak tertulis data kebutuhan kayu tersebut.
Ada potensi laporan produksi pelet kayu perusahaan cuma dari kayu karet, tidak mencantumkan jenis kayu lain. Sehingga mereka lolos dari kewajiban membayar pajak provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR).
Kebutuhan kayu RPSL sedikitnya 50 persen dari total bahan baku 104.400 ton. Dalam hitungan estimasi, apabila dikonversi menjadi 141,205 meter kubik. Dengan pembayaran pajak terendah yakni Rp75.000/kubik, setiap tahun negara kehilangan Rp10,59 miliar.
Kerugian lain adalah emisi karbon. Dengan kebutuhan kayu minimal 50.000 ton, maka deforestasinya sekitar 4.000 hektar setiap tahun.
Menurut Forest Watch Indonesia penebangan 1 hektar hutan akan melepas 146,14 ton emisi karbon.
“Dengan angka itu, maka pelepasan karbon karena RPSL mencapai 584,560 ton. Itu baru dari deforestasi, belum kita menghitung emisi dari pembakaran di pembangkit listrik dan pabrik pelet kayu,” kata Feri.
Pemanfaatan biomassa dari hutan maupun limbahnya untuk energi, justru dapat memperburuk krisis iklim. Emisi dari pembangkit biomassa, diperkirakan sama besarnya dengan PLTU.
Perusahaan ini dari hulu sampai hilir bermasalah. Meskipun mereka mengklaim mendukung kebijakan transisi energi, justru berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
“Pemerintah harus segera evaluasi dan tutup RPSL jika terbukti melakukan deforestasi,” kata Feri.
Selaras dengan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari, Sodiq yang mengatakan kayu bungur dan rengas tidak termasuk kayu budidaya, melainkan rimba campuran sehingga harus dikenakan PSDH dan DR. “Ada tarifnya per jenis kayu dan diameter, semua
bisa beda-beda,” katanya.
Hutan yang terus menyempit, sambung Sodiq setiap perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan, harus transparan dan bertanggung jawab. Selain untuk menghindari adanya deforestasi, juga tidak menyebabkan kerugian negara.
Apabila merujuk pada data KKI Warsi, pada 1973, tutupan hutan Jambi tercatat 3,4 juta hektare. Setengah abad kemudian, deforestasi membuat hutan musnah dan tersisa 922.891 hektare. Hutan alam terakhir tersisa di empat taman nasional dan kawasan penyangga.
Sementara emisi di Sumatera terus meningkat. Dokumen RUPTL menyebut proyeksi peningkatan dari 37,1 juta ton pada 2018 menjadi 77,9 juta ton pada 2027. Sebaliknya emisi dari sektor energi akan turun dari 0,877 tonCO2/MWh pada 2018 menjadi 0,809 tonCO2/MWh pada 2027, jika transisi energi berjalan mulus.
Dampak Deforestasi
Perusahaan sawit yang bekerja sama dengan RPSL berada di lahan gambut dan mengalami kebakaran. Mereka tidak sepenuhnya mematuhi regulasi terkait restorasi gambut: dengan memasang sekat kanal dan menjaga tinggi muka air 40 sentimeter.
Dampak eksploitasi hutan dan gambut, terjadi kebakaran seluas 6.798 hektare (Juli-Agustus 2024). Lebih separuh lahan yang terbakar berada di konsesi perusahaan sawit dan hutan tanaman industri. Angka ini akan terus bertambah seiring musim kemarau, yang memicu krisis air di lahan gambut.
Aswandi, Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Jambi memprediksi kawasan pesisir timur Jambi, terancam tenggelam pada 2030 mendatang, apabila lahan gambut terus terbakar. Fenomena subsiden (penurunan muka tanah) dan dekomposisi (kerusakan gambut) membawa petaka.
“Kubah gambut itu, analoginya seperti bubur panas. Apabila terus dimanfaatkan, maka dia akan mengalami subsiden dan dekomposisi,” kata Aswandi yang sudah menekuni bidang keilmuan ini selama 20 tahun.
Gambut dan air berteman. Apabila air dikeluarkan melalui kanal, kata Aswandi, tentu gambut akan hilang dengan cepat. Sebab hampir 80 persen kandungan gambut adalah air. Apabila gambut kering karena deforestasi dan kanalisasi, maka mudah terbakar.
Penelitian gabungan antara lembaga yakni Delv Hidrolik, Belanda, Singapore-Delft Water Alliance (SDWA) dan Universitas Jambi, menunjukkan konektivitas hidrologi gambut terganggu karena fenomena subsiden. Hal ini melepas banyak karbon. Kemudian sinaran mentari 12 jam, akan mempercepat kerusakan gambut.
Studi yang dilakukan 2004-2020, menunjukkan terjadi subsiden hingga 150 cm terhadap perkebunan yang dibuka periode 1992-2002. Lalu pada periode 2003-2009 subsiden sebesar 72 cm. Dan periode 2009-2020 sebesar 5 cm, sehingga total seluruhnya sudah subsiden 272 cm pada lahan yang sama.
“Kalau air laut sudah masuk ke daratan, maka tidak bisa lagi digunakan untuk lahan pertanian,” katanya.
Masuknya air laut ke daratan, selaras dengan prediksi yang disebut dalam analisis Climate Central, Inc. Analisisnya menunjukkan pada 2030 tiga kabupaten seperti Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi bagian timur tenggelam.
Tiga wilayah ini, wilayahnya didominasi gambut dalam. Selain kerusakan gambut, perubahan iklim mempercepat kenaikan muka air laut. Ketika level tahun dinaikkan pada 2050, maka air memasuki Kota Jambi. Sedangkan pada 2070 hampir semua Kota Jambi terendam air.
Aktivitas RPSL diduga menjarah kayu dari lahan gambut. Perusahaan sawit yang memasok bahan baku ke RPSL, juga melakukan kanalisasi di lahan gambut. Jika perusahaan ini terus beroperasi, maka kebutuhan kayu akan terus meningkat.
Fokus Pelet Kayu
Humas Perusahaan PT RPSL, Lestari Defri mengaku mendukung rencana transisi energi pemerintah. Sehingga selama lima tahun mereka memasok energi bersih dari biomassa ke PLN.
Walau begitu mereka akhirnya menyerah dengan harga rendah dari PLN. Jika mengacu kontrak 2014, tarif setrumnya melorot lebih 50 persen. Untuk mencegah kerugian dari jual setrum, maka RPSL memilih fokus produksi pelet kayu.
“Kami sudah putus kontrak pasokan listrik ke PLN pada 2019 lalu. Kami kini fokus memproduksi pelet kayu,” kata Defri.
Meskipun sudah tidak memasok listrik ke PLN, sambung Defri pihaknya masih memproduksi listrik dari pembangkit biomassa, untuk kebutuhan sendiri. Artinya aktivitas RPSL tidak menggunakan energi kotor.
Manager Area PLN Jambi, Ediwan mengatakan urusan pemutusan kerja sama dengan PT RPSL terkait energi bersih, diputuskan oleh pusat. Perannya hanya sebatas mengelola distribusi listrik.
Lantaran tidak lagi bekerja sama dengan PLN, hampir dua tahun perusahaan yang didanai investor asing ini vakum. Mereka baru memproduksi pelet kayu pada 2022 sampai sekarang.
Ia menyadari berusaha di bidang energi bersih, perusahaannya harus memiliki komitmen tanpa deforetasi. Untuk memastikan semua kayu legal, dari banyak sumber mereka minta dokumen resmi yang disahkan pemerintah, apabila mau menjual kayu ke RPSL.
“Ya kami ambil bahan baku dari sawmill. Hampir 90 persen dari wilayah Muarojambi dan Kota Jambi. Semua pakai pihak ketiga yang telah memiliki izin,” kata Defri.
Dari total kebutuhan kayu sebanyak 104.400 ton sesuai izin di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), RPSL hanya bisa mengumpulkan 60 persen. Pasalnya ada banyak kendala mulai dari cuaca dan sawmill yang kadang tidak beroperasi karena kekurangan bahan baku.
Kebutuhan bahan baku untuk produksi pelet kayu memang setengahnya dari sawmill, lalu sisanya membeli kayu racuk dan karet dari masyarakat.
“Itu kan sampah ya. Limbah bagi sawmill tidak dipakai lagi dan itu yang kami beli,” kata Defri.
Kendati demikian, Defri tidak bisa memastikan legalitas kayu dari sawmill. Ia hanya bilang, jika RPSL mematuhi regulasi dan telah mengantongi izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dan sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).
“Asal kayu kita ada tim auditor kehutanan. Semua dokumen-dokumen itu pasti dicek, jadi tidak mungkin ada kayu ilegal masuk ke kita,” kata Defri.
Terkait sumber kayu RPSL tidak sesuai dengan dokumen Amdal, Defri menegaskan sesuai aturannya memang bisa diubah, tergantung kebutuhan. “Mana cukuplah sumber kayu dari empat daerah itu,” kata Defri.
Jual ke Korea Selatan
Selama lebih dua tahun produksi pelet kayu, RPSL memenuhi permintaan dari pasar Korea Selatan. Negeri gingseng sedang menjalankan komitmennya agar terdepan di Asia dalam transisi energi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat data ekspor pelet kayu mencapai 14.513 ton pada 2022, tahun berikutnya melorot menjadi 12.042 ton. Lalu data triwulan tahun ini, tercatat 1.955 ton. Dari total ekspor itu, nilainya mencapai 3,09 juta dolar.
Permintaan pelet kayu dari Korea, sambung Defri memang tinggi. Ekspornya lebih lima kali dalam sebulan. Pelet kayu dikirim melalui Pelabuhan Talang Duku dengan kapasitas 30 kontainer, untuk satu pembeli. “Ada beberapa buyer yang beli wood pellet dari kita,” kata Defri.
Korea sedang fokus mengurangi ektraksi batu bara, kata Defri. Hal itu berdampak dengan tingginya permintaan pelet kayu. Produk ini, kata dia kualitasnya setara dengan batu bara, namun lebih ramah lingkungan.
Defri pun mengklaim untuk Sumatera, RPSL menjadi pengekspor pelet kayu terbesar ke Korea. Kemudian menggunakan bahan baku dari kayu-kayu, yang ada di Jambi.
Untuk angka produksi, Defri tidak memberikan data secara rinci, melainkan data global. Menurutnya dari 104.400 ton target produksi dalam dokumen Amdal, produksi baru setengahnya.
“Kita banyak kendala juga, terkadang bahan baku yang tergantung cuaca dan mesin yang kadang rusak. Jadi tidak bisa konsisten produksi 288 ton setiap harinya,” kata Defri.
Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menuturkan perusahaan yang memproduksi pelet kayu dan tidak memiliki lahan sendiri, berpotensi serampangan mencari kayu dari sumber-sumber ilegal.
Untuk bertahan bahkan menambah volume produksi, RPSL diduga akan terlibat dalam aktivitas ilegal ‘pencucian kayu’. Dengan memanfaatkan sawmill untuk melegalkan kayu dari aktivitas pembalakan liar. “Ini modus baru deforestasi di Jambi,” kata Anggi.
Apabila bisnis ini minim pengawasan, maka deforestasi menjadi tak terkendali. Selanjutnya berpotensi menyebabkan kerugian negara dari sektor kehutanan, karena tidak tercatat di sistem Informasi legalitas kayu (SILK).
Ekspor RPSL ke Korea Selatan diduga tidak tercatat di data KLHK. Menurut Anggi data ekspor pelet kayu ke Korea, hanya ada tiga provinsi yakni Gorontalo, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Temuan baru ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Anggi mencermati modus baru deforestasi di Jambi dengan serius. Ia menilai Korea mendapatkan citra energi bersih dari pelet kayu, sementara hutan-hutan di Jambi terus dibabat. “Ini namanya kolonalisasi iklim,” kata Anggi.
Ada dampak aktivitas perusahaan energi bersih, FWI mendorong pemerintah melakukan audit, monitoring dan evaluasi secara ketat. Jika menentang agenda nasional maupun global dalam menangani krisis iklim dan dampak sosial, maka sebaiknya ditutup saja.
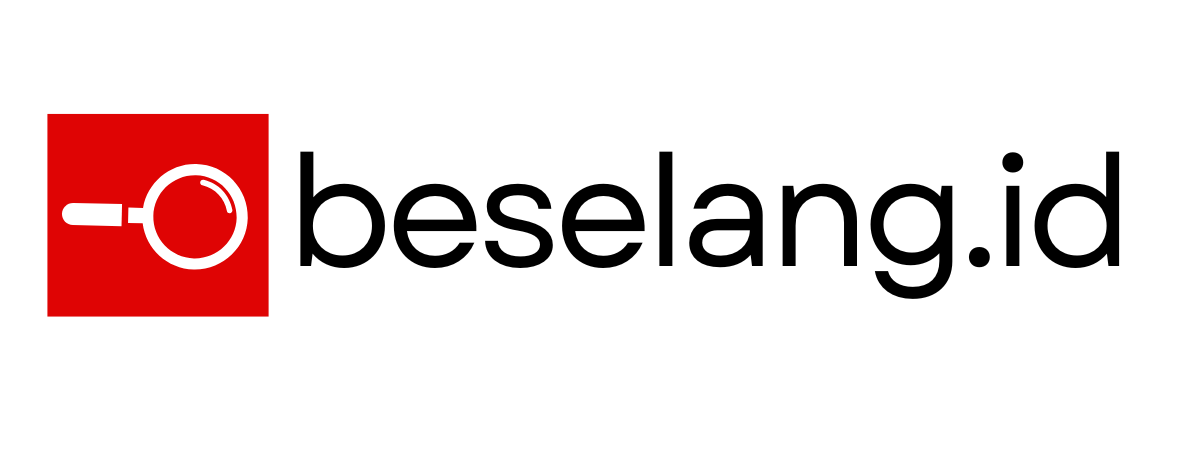









Leave feedback about this