KALA truk raksasa proyek melintasi jalan nasional, rumah-rumah berselimut debu. Getaran kecil menembus dinding menyelinap ke ruang tamu. Sepelemparan batu di bawahnya, aliran sungai yang deras melamban dan terus meninggi. Tembok lebih 20 meter menghadang air di badan sungai. Di balik tembok, truk raksasa, crane dan alat berat menderu. Lima rumah yang terhimpit jalan dan bendungan sungai, semakin lusuh. Pemiliknya merasa rapuh.
Gustina (57) penghuni rumah di antara sungai dan jalan hanya bisa pasrah. Tangan keriputnya tak mampu mencegah pembangunan. Seorang diri di masa tua meruntuhkan nyalinya untuk menghalau barisan truk raksasa perusahaan.
“Kata mereka (perusahaan) aman, aman tak ada masalah. Namanya orang kecil ini, mau ngadu, ngandu ke mana kami tidak tahu,” kata Gustina di rumahnya, Dusun Kaliangga, Desa Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi, akhir Februari lalu.
Perempuan yang baru beberapa bulan kehilangan suami ini mengaku dirundung ketakutan. Perusahaan mengklaim rumahnya aman, kenyataannya seluruh ruangan di rumahnya retak-retak. Mulai dari ruang tidur, tamu dan dapur mengalami keretakan serius. Tanah di belakang rumahnya berkali-kali longsor. Rumah yang berada di puncak tebing sungai dan berhadapan langsung dengan jalan nasional, tempat truk raksasa melintas ternyata mengandung bahaya.
Dampak dari ledakan dinamit pembangunan terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin di tubir Sungai Batang Merangin, membuat 33 rumah radius terdekat retak.
Pembangunan mega proyek PLTA Batang Merangin dikerjakan PT Kerinci Merangin Hidro, anak usaha dari Kalla Grup. Bahkan PLN telah meneken perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) dengan perusahaan milik Jusuf Kalla, pada Akhir 2018 lalu. Pembangunan sempat terhenti pada 2010 lalu, karena PLN meminta perusahaan untuk mengubah kapasitas dari awalnya 150 Megawatt.
Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2020 lalu, berkata lain. Pembelian listrik kepada PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) dengan metode penunjukkan langsung oleh PLN, telah membuat kerugian negara sebesar Rp15,55 triliun. Sementara dalam kontraknya, PLTA Batang Merangin hanya wajib beroperasi saat beban puncak selama lima jam, mulai pukul 18.00-23.00 WIB mengalirkan setrum ke PLN regional Sumatera.
Dengan kapasitas 350 MW, setrum dari PLTA Batang Merangin akan memasok listrik ke sistem Sumatera. Aliran setrum sebesar 1.280 giga watt hour per tahun ini, hanya mengalir saat beban puncak di PLN Regional Sumatera. Proyek dengan nilai investasi Rp 13,4 triliun ini, menyumbang kurang dari 10 persen dari beban puncak listrik di Sumatera yakni sebesar 6.928 megawatt.
Dengan pendanaan begitu besar, seharusnya mempermudah pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak. Sebagian besar warga memang sudah menerima dana kompensasi. Namun Agustina sudah berjuang enam bulan, sampai suaminya meninggal kompensasi belum juga turun dari perusahaan.
“Sampai suami saya (meninggal) Mas, dana kompensasi ini tidak diberikan perusahaan. Kami ini warga kecil, tangan di bawah. Ya pasrah saja, mau dikasih atau tidak,” kata dia.
Keretakan di kamar tidurnya begitu parah. Sudah terbentuk lubang yang menganga selebar dua jari orang dewasa dan panjang lebih dua meter. Sementara aktivitas truk raksasa dengan kapasitas lebih dari 30 ton yang melintas menimbulkan getaran.
“Terasa getarannya. Kalau malam itu lebih kuat. Saya tidur sendirian. Takut sewaktu-waktu dinding kamar saya ini ambruk,” kata dia.
Di ruang tamu, Tuti sedang merawat bayinya yang berusia tiga bulan. Dari ruangan ini getaran truk raksasa perusahaan yang melintas menimbulkan getaran skala kecil. Di atas kepala bayi yang tidur pulas itu, ada jejak ledakan dinamit terowongan PLTA.

Serupa dengan tetangganya Agustina, retak di rumah Tuti serius di seluruh ruangan dan belum menerima kompensasi. Dia sudah melapor ke perusahaan tiga bulan lalu.
“Anak kami ini masih umur 3 bulan. Kadang terbangun dengar suara truk. Terkejut dia. Kami juga khawatir dindingnya tiba-tiba ambruk, karena retakannya tinggi dari atas sampai bawah,” kata dia sembari memasang kain penutup telinga anaknya.
Nihil transparansi genangan bendungan
Pada siang yang terik, Amri warga Desa Lubuk Paku kaget patok bewarna merah putih menancap di ladangnya. Lelaki itu sempat naik pitam, karena pemasangan patok tanpa izin. Ketakutan Amri terbit saat adanya patok perusahaan. Pasalnya, masyarakat Desa Lubuk Paku masuk dalam area genangan PLTA. Hanya saja, perusahaan belum pernah memberikan informasi terkait luas genangan dan berapa rumah yang akan tenggelam.
“Tidak tahu Pak. Perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi luas genangan dan berapa rumah yang akan tenggelam. Tapi sudah ada belasan rumah yang diganti rugi,” kata Amri.
Rumah Amri berada di bantaran sungai, jaraknya hanya 1 meter dari batas terakhir tanah dan rumah di kampung yang dibebaskan perusahaan. Tidak adanya pemberitahuan dari pihak perusahaan terkait rencana bendungan, membuatnya gusar. Berada dalam radius 1 meter dengan genangan air bendungan, membuatnya takut.
“Saya tidak tahu, bagaimana cara mereka mengukur untuk rumah atau ladang yang memenuhi syarat dibebaskan. Tapi saya takut, untuk hidup berdekatan dengan air bendungan. Saya berharap mereka ganti rugi rumah saya, karena kami sekeluarga mau pindah,” terangnya.
Dia menuturkan lebar patok di sisi kiri kanan sungai sekitar 200 meter. Sementara panjangnya sudah lebih dari 2 kilometer. Dengan demikian luasan genangan yang berada di Desa Lubuk Paku bisa mencapai 400 hektar.
Suriwati, warga lainnya perempuan berusia 67 tahun ini menuturkan rumahnya yang berada di pinggir Sungai Batang Merangin sudah dibebaskan perusahaan Oktober 2022 lalu. perusahaan tidak mengatakan rumahnya akan ditenggelamkan. Tetapi dengan keadaan berada di bibir sungai, Suriwati dan keluarga telah berjaga-jaga. Rumah yang dibebaskan sudah ditinggalkan dan kini dia membuat rumah baru, yang jauh dari sungai.
“Saya tidak tahu, akan tenggelam atau tidak. Perusahaan tidak pernah bilang begitu. Tapi kami berjaga-jaga. Kini kami sudah pindah buat rumah baru,” katanya.
Dia menuturkan pemilik belasan rumah lain yang sudah dibebaskan perusahaan, masih ada yang menempati rumahnya. Lantaran belum menemukan tempat yang cocok, yang dekat dengan ladang mereka.
Farida, perempuang yang sudah 40 tahun tinggal di Dusun Kaliangga, Desa Batang Merangin mengaku tanahnya yang berada di kawasan genangan PLTA belum diganti rugi. Dia mengaku belum mengetahui tanah di belakang rumahnya akan tenggelam.
“Saya tidak tau akan ada genangan air (menunjuk) di sini, belakang rumah saya. Iya takut lah, karena ada genangan air yang dalam dan luas. Anak-cucu saya kan mainnya di sini. Kalau disuruh pindah, kalau cocok tempatnya, ya maulah. Asal kami tidak rugi mereka (perusahaan) juga tidak rugi,” kata Farida.
Kegusaran Farida bukan tanpa alasan. Ketika hujan besar air datang dari seberang jalan, mengalir jatuh ke belakang rumahnya, tempat Sungai Batang Merangin berada. Tanah di samping rumahnya sudah longsor, sebab kayu-kayu besar yang berjarak sekitar 5 meter dari rumahnya, sudah ditebang.
“Kalau tanah di bawah situ, semua sudah diganti rugi. Tapi kami belum. Longsor di tanah kami karena kayu-kayu besar ditebang. Sudah dilaporkan ke perusahaan, tapi mereka tidak ada tindakan,” kata Farida menjelaskan.
Lokasi rumah Farida terjepit sungai dan jalan. Jarak keduanya kalau ditarik garis lurus hanya sekitar 10-15 meter.
Pembebasan lahan juga banyak masalah, kata Amri. Harganya sangat bervariasi ada Rp15.000 per meter ada yang Rp25.000 per meter. Bahkan ada dua lokasi tanah, perusahaan belum membayar uang ganti rugi.
Pengukuran tanah, sambung Amri sangat bermasalah. Lantaran pada bantaran sungai yang curam, warga mengukur luasnya 5.000 m2, sementara menurut perusahaan luasnya hanya 2.000 meter persegi. Dengan demikian perusahaan hanya membayar Rp30 juta, seharusnya Rp75 juta.
“Perusahaan itu mengukurnya pakai GPS. Jadi tanah yang miring itu ditembak lurus. Sementara saya ukur tanah secara manual. Hasilnya jauh berbeda,” kata Amri.
Ketika membebaskan lahan, perusahaan tidak memberikan informasi kepada warga, terkait mengapa rumah dan ladang mereka dibebaskan. Sampai sejauh ini, belum ada warga yang mengetahui, seberapa luas genangan dan seberapa banyak rumah yang akan tenggelam.
Kepala Desa Batang Merangin, Sumino mengaku telah letih melakukan perlawanan dengan pihak perusahaan. Laporannya terkait sungai-sungai kering dan keruh dampak pembangunan PLTA Batang Merangin tak digubris perusahaan, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
“Kering lah airnya. Aliran air sungai sempat dimatikan. Bersamaan dengan pembangunan terowongan. Air itu lari ke terowongan. Saya pernah masuk, banjir itu terowongan,” kata Sumino.
Perlawanan Sumino berangkat dari keinginan adanya transparansi pihak perusahaan kepada warga. Sehingga warga tidak minim informasi terkait aktivitas perusahaan. Warga tidak ada yang tahu, beberapa meter di rumahnya itu perusahaan menyimpan bahan peledak dinamit.
“Kalau ada insiden itu semua warga habis, terdampak ledakan seperti bom. Saya sudah protes. Gudang bahan peledak itu dipindah. Tapi saya sendirian, ditekan sana sini, saya tak kuat juga. Alhamdulillah, tidak ada korban. Sekarang gudangnya masih ada, tapi bahan peledaknya sudah habis digunakan untuk bangun terowongan,” kata Sumino.
Informasi terkait genangan yang terdampak langsung kepada warga Desa Batang Merangin, lokasi ring satunya pembangunan PLTA itu tidak ada. Perusahaan tidak membuka data itu kepada warga. Sehingga warga hidup di bawah bayang-bayang ketakutan.
PLTA ini juga diduga kuat terkait dengan pertambangan ilegal. Efriantoni, Pemuda Pecinta Lingkungan di Kecamatan Batang Merangin mengaku heran dengan perusahaan yang tidak teliti, menyaring sumber pasir dan batu. Kebanyakan perusahaan yang memasok pasir dan batu (Sirtu) ke perusahaan berasal dari penambangan galian C secara ilegal.
“Mereka ini (perusahaan) memang terdaftar secara legal di pemerintahan. Tapi lokasi tambangnya itu berbeda dengan yang dalam dokumen izin. Yang ambil Sirtu di Kecamatan Pangkalan Jambu itu, bekas penambangan emas ilegal,” kata Efriantoni.
Pasokan sirtu ke PLTA dipasok dari Kecamatan Pangkalan Jambu, Siulak dan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, perusahaan menggunakan material bebatuan dari terowongan. Lelaki yang tinggal di Tamiai menyebut material dari terowongan itu ilegal, kalau digunakan perusahaan. Sebab, dalam membangun terowongan itu mereka tidak melakukan pembebasan tanah kepada masyarakat.
Penggunaan material Sirtu perusahaan tidak boleh dipandang remeh. Sebab dengan material itu, mereka membangun terowongan dengan panjang lebih dari 11 kilometer, kemudian membangun bendungan setinggi puluhan meter dan membuat turap di bantaran sungai berkilo-kilometer.

Jangan sampai untuk menghasilkan energi bersih, perusahaan malah merusak lingkungan dengan membeli material di tempat yang ilegal dan bukan termasuk kawasan pertambangan yang sah diatur pemerintah.
Dengan mengambil material di tempat ilegal, maka potensi merusak lingkungan semakin tinggi. Hal senada disampaikan Kabid Pertambangan dari ESDM Provinsi Jambi, Novaizal mengamini di lokasi penambangan material yang disetor ke PLTA, tidak mengantongi izin galian C seperti di di wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin dan Kecamatan Siulak, Kerinci.
“Untuk wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu, tidak ada izin Galian C karena sudah menjadi pertambangan emas tanpa izin,” kata Novaizal singkat.
Aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangkalan Jambu terjadi sejak 2010 lalu, sampai sekarang. Penelitian Kumorotomo dari Universitas Gadjah Mada menyebut luas pertambangan sekitar 655 hektar. Penambangan menimbulkan banyak masalah, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, konflik, sumber penyakit dan adanya korban jiwa.
Pengambilan material pasir dari lokasi penambangan emas ilegal ditanggapi dingin oleh Teguh, Direktur Bukaka. Katanya kalau memang ada informasi dan bukti mengenai sumber sirtu dari tambang ilegal, kita akan tindak lanjuti.
Selanjutnya, jika benar material didapatkan secara ilegal, maka ini menjadi pelanggaran aturan. Setiap penggalian material perlu izin usaha pertambangan (IUP) sebagai syarat legalitas, termasuk proses pengangkutan dan jual-beli juga perlu izin, kata Zakki dari Tren Asia.
Transisi energi harus menyeluruh, kata Zakki agar PLTA tidak hanya menjadi transisi bisnis dan teknologi tanpa peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian energi bersih yang dihasilkan, terbukti bersih dari hulu sampai hilir.
Megaproyek Energi Bersih Tak Boleh Merusak
Sebagai ujung tombak energi terbarukan, kata Manager Komunikasi Walhi Jambi, Eko M Utomo menuturkan seharusnya pembangunan PLTA tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, dalam pembangunan tidak merusak lingkungan.
Dengan mengambil material dari area pertambangan emas ilegal dan lokasi lain tanpa izin yang sah dari pemerintah, maka pihak PLTA Batang Merangin memberi karpet merah, terhadap tindakan merusak lingkungan.
“Aktivitas perusahaan sudah merubah bentang sungai dan alam, tentu ini sudah mengganggu dan menghilangkan hak dasar warga, untuk mendapatkan lingkungan yang aman, bersih dan sehat,” kata Eko.
Pelanggaran hak dasar manusia ini, dapat mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya rumah warga yang retak, itu harus mendapat kompensasi, debu dari truk raksasa mengancam kesehatan warga, jangan diabaikan.
Tidak hanya itu, masyarakat yang menggantungkan hidup dari Sungai Batang Merangin terganggu karena sungai keruh, kering dan ikan menghilang. Bahkan ada sungai yang dangkal dan tertimbun longsoran nyaris seluruh badan sungai. Pembuatan bendungan bisa memicu kepunahan spesies ikan semah endemik. Ini juga terabaikan.
Dia mendorong pemerintah mengkaji ulang izin dari PLTA Batang Merangin. Kemudian memastikan dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan PLTA minim. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Walhi Jambi akan menolak pembangunan PLTA.
Selain itu, kata Eko Jambi saat ini sudah surflus setrum. Hanya di daerah terpencil di pegunungan dan pesisir, ada beberapa desa yang belum teraliri listrik. Untuk mengakses itu, pemerintah sudah mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2019, yang mengatur solusi pembangunan listrik untuk daerah pedesaan di Jambi, dengan memperbanyak energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), panel surya serta biogas.
Perkataan serupa diucapkan Kabid Kelistrikan Dinas ESDM Jambi, Yussvinoza. Ia menuturkan tingkat elektrifikasi Jambi saat ini sudah mencapai 99,99 persen. Dengan demikian pasokan setrum di Jambi sudah melebihi kebutuhan listrik di Jambi. Ketersediaan daya listrik di Jambi, saat ini mencapai 454 MW. Sementara kebutuhan listrik bahkan saat beban puncak hanya sekitar 338 MW.
Jambi memang surflus setrum, kata dia tetapi pemerintah terus mendorong transisi energi baru terbarukan. Apakah PLTA Batang Merangin akan menggantikan energi fosil, Yussvinoza enggan berkomentar. “Kalau PLTA itu urusan pemerintah pusat,” kata dia singkat.
Manager Riset Tren Asia, Zakki Amali, berkata serupa. PLTA memang menjadi salah satu tumpuan untuk menggantikan energi kotor batubara. Tapi PLTA seperti apa yang dapat memenuhi aspek keadilan lingkungan? Ini tidak pernah jadi pembahasan serius, kata Zakki.
Lokasi pembangunan PLTA bukanlah tanah kosong yang tidak dihuni oleh masyarakat sama sekali. Ada keanekaragaman hayati yang juga penting. Sejauh ini pembangunan PLTA, seperti grup Kalla ini menimbulkan dampak bagi masyarakat yang belum terselesaikan seperti PLTA Poso.
Pembangunan PLTA ini, menerima protes keras dari warga lokal, karena besaran kompensasi yang tidak adil. Itulah mengapa transisi energi seharusnya tidak meninggalkan aspek keadilan, karena tanpa itu maka yang terjadi hanya perpindahan teknologi pembangkit listrik dari fosil ke “bersih”.
Untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, perusahaan tidak hanya harus transparan, tetapi wajib akuntabel dan partisipatif. Setidaknya ada Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Studi Larap untuk melihat rencana akuisisi tanah dan mitigasinya, menggambarkan posisi masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat juga perlu didengar dan dihormati.
Proses pembangunan PLTA pada umumnya mengeluarkan emisi mulai dari aktivitas mesin sampai penggunaan hutan untuk area genangan. Bahkan setelah dibangun tampak bersih energinya, tetapi ada aspek lain seperti gas metana.
Gas ini tidak terlihat mata, tapi bisa muncul dari bendungan. Gas metana ini juga bisa mempengaruhi pemanasan global. Hanya saja emisi gas metana belum menjadi perhitungan dari proyek PLTA.
“Ke depan perlu memasukkan perhitungan emisi gas metana dari bendungan,” kata Zakki.
Sementara itu, Teguh Wicaksana Sari, Direktur Bukaka, bagian dari Kalla Grup menuturkan keberadaan PLTA Batang Merangin, untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Sehingga akan mengurangi ketergantungan dengan energi fosil.
Berdasarkan perjanjian jual beli listrik dengan PLN hingga November 2025, kata Teguh, pihaknya memasok 350 MW ke sistem grid seluruh Sumatera. Seluruh wilayah di Sumatera, menerima pasokan listrik dari PLTA Batang Merangin.

Sejak beroperasi pada 2018 lalu, PLTA Batang Merangin telah memberdayakan 1.600 tenaga kerja lokal. Efek domino dari perusahaan adalah adanya pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi selama konstruksi.
“Pengusaha-pengusaha lokal tumbuh seperti kontraktor, supplier material alam dan rumah makan. Ketika usaha ini beroperasi, otomatis menjadi sumber PAD,” katanya.
Ia menegaskan tidak ada dampak dari pembangunan, karena tidak menimbulkan genangan. hal ini disebabkan cara kerja PLTA Batang Merangin menggunakan sistem run of river.
“Pembangunan di lahan seluas 200 hektar, yang berada di dua desa. Kami tegaskan, tidak ada dampak pada dua desa tersebut, karena tidak ada relokasi penduduk ataupun desa tergenang,” kata Teguh.
Sejauh ini, kontribusi Kalla Grup terhadap energi nasional sudah mencapai 600 MW dari PLTA Poso dan Toraja yang sudah beroperasi dan akan membangun 1.000 MW kembali, pada 5-10 tahun ke depan.
Merampas Tanah Adat
Pembangunan mega proyek PLTA dengan kapasitas 350 megawatt, tidak hanya menimbulkan persoalan bagi warga sekitar, seperti Agustina dan Tuti. Hal senada dirasakan pentolan masyarakat adat Muaro Langkap, Depati Mukhri Soni, yang naik tahta 2021 lalu.
“Saya dibenci keponakan, keluarga sendiri. Biarlah. Saya tanggung. Saya mau mengembalikan sirih ke gagangnya, pinang ke tampuknya. Ini demi kebaikan semua orang di masa sekarang dan mendatang,” kata Datuk Mukhri di rumah induk sko dengan mata berbinar.
Aturan sepanjang adat telah berlaku kepada pengelola PLTA Batang Merangin pada 2010 lalu. Namun setelah Depati Ahmad S turun tahta, perusahaan gencar melakukan pendekatan pada depati yang baru, Helmi Muid.
Misi perusahaan, kala itu kata Datuk Mukhri ingin mengalihkan kepemilikan tanah adat menjadi milik perusahaan. Sudah ada 20 hektar tanah di kawasan adat yang berstatus sertifikat hak milik (SHM). Sehingga telah terjadi jual beli, yang intinya tanah adat itu kini milik perusahaan.
Atas kejadian itu, masyarakat adat Muaro Langkap menggugat Helmi Muid, Direktur PT Kerinci Merangin Hidro dan Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci ke pengadilan perdata. Gugatan yang telah sidang perdana pada Senin (23/5/2022) sampai kini belum ada keputusan.
“Karena tergugat pertama meninggal dunia, kita akan ajukan ulang. Kita akan perjuangkan tanah 20 hektar itu bukan milik pribadi, tetapi atas nama masyarakat adat Muaro Langkap,” katanya.
Perampasan tanah adat yang terjadi, tidak hanya di Jambi melainkan jamak di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat total 8,5 juta hektar kawasan adat di Indonesia mengalami perampasan. Angka tersebut akumulasi perampasan selama lima tahun terakhir.
“Perampasan dilakukan pihak-pihak yang bergerak di sektor perkebunan, kawasan hutan negara, pertambangan, dan pembangunan proyek infrastruktur,” kata Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi melalui sambungan telepon.
Dampak dari perampasan meletus konflik masyarakat adat, sebanyak 301 kasus yang mengakibatkan 672 jiwa warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dan perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektar.
Untuk membela hak-hak masyarakat adat, kata Erasmus pihaknya telah mengembangkan model advokasi kebijakan, dengan pendekatan bantuan hukum struktural yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Kemudian gencar kampanye publik dan aksi pembelaan di lapangan, memperkuat hukum lembaga adat, kawasan adat, dan kearifan lokal.
Ironi, kata Erasmus perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, kini berjalan mundur. Hukum tidak menjawab persoalan kami, tetapi mempercepat perampasan tanah-tanah adat, melalui UU Minerba dan Cipta Kerja.
“Undang-undang yang baru ini condong kepada kepentingan korporasi dan proyek strategis nasional, dibanding hak-hak masyarakat adat,” kata Erasmus.
AMAN begitu getol memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, lantaran menyadari adanya hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya. tidak hanya bernilai ekonomi dan ruang hidup, tetapi juga teologi (kepercayaan) yang terhubung dengan leluhur dan Tuhan.
Mengapa tanah adat tidak boleh menjadi hak milik? Secara turun temurun tanah adat Depati Muaro Langkap dari Tamiai sampai Perentak, diwariskan ke anak jantan dan betino, sebutan untuk masyarakat adat Muaro Langkap.
Semua anak jantan dan betino boleh memanfaatkan tanah adat itu, bahkan sejak dia lahir sampai meninggal. Syaratnya satu tidak boleh menjadi hak milik. Semua masyarakat adat mematuhi aturan tidak tertulis itu, selama ribuan tahun.
Ia mencontohkan pada tahun 1924 lalu, penjajah Belanda menerapkan ajum arah dari orang adat, dengan memotong 40 kerbau, sebelum membuka hutan di kawasan adat untuk perkebunan kopi. Termasuk status tanahnya hanya pinjam pakai atau hak guna usaha (HGU).
“Orang-orang Belanda yang kita kenal penjajah itu lebih bijaksana, mereka meminta izin dan ajum arah (pedoman) dari orang adat. Ketika mau bangun perkebunan kopi (sekarang lokasi PLTA). Mereka mau potong 40 kerbau dan pinjam pakai atau Hak Guna Usaha (HGU) dari Depati Muaro Langkap artinya tidak menjadi hak milik,” kata Datuk Mukhri menjelaskan.

PLTA ini sementara, Muaro Langkap itu tatatan selamanya. Dengan konsep pinjam pakai, maka tanah adat tetap menjadi milik anak-cucu masyarakat adat Muaro Langkap. Terkait sistem pembayaran pinjam pakai, tidak melulu soal uang. Melainkan bisa mendirikan gedung, menciptakan peluang ekonomi bagi anak jantan dan betino.
Kearifan lokal Terlewatkan
Datuk Mukhri ingin mengembalikan sirih ke gagangnyo secara dingin, artinya tidak merepotkan perusahaan. Kendati demikian untuk menjemput yang tertinggal dan mengumpulkan yang terserak, perusahaan harus bersedia dijatuhi denda adat.
Sebelum ke sana, perlu diketahui, kata Datuk Mukhri sebelum negara Indonesia ini ada, Depati Muaro Langkap adalah negara yang berdaulat. Tidak pernah berada dalam kekuasaan Kerajaan Melayu maupun Pagaruyung.
Sehingga pada tahun 1296 terbentuk negara konfederasi Depati Empat Alam Kerinci, dengan pusat pemerintahan di Sanggaran Agung. Disebut demikian karena merupakan gabungan dari negara-negara berdaulat; 4 diateh 3 dibaruh.
Lebih lanjut dia menjelaskan 4 diateh adalah Depati Muaro Langkap Tamiai, Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, Depati Biangsari Pengasih dan Depati Atur Bumi Hiang. Kemudian untuk 3 dibaruh adalah Depati Setio Nyato Tanah Renah, Depati Setio Rajo Lubuk Gaung, Depati Setio Beti Nalo Tantan.
Masyarakat adat Muaro Langkap menyadari tidak boleh ada negara dalam negara. Mereka pun berbesar hati berada dalam kekuasaan Negara Indonesia. Untuk membuktikan itu, mereka sudah menyerahkan puluhan ribu hektar hutan, agar masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Kendati tanah adat mereka sudah menyusut tajam, sambung Datuk Mukhri demi kepentingan orang banyak dan energi bersih, pihaknya membolehkan tanah adat dikelola pihak PLTA Batang Merangin, dengan syarat bukan hak milik dan menghormati kearifan lokal.
Harus dijatuhi denda adat karena pihak perusahaan melewatkan kearifan lokal. Untuk membuka hutan perusahaan Belanda harus memotong 40 kerbau. Sebaliknya, pihak PLTA ketika melakukan pembangunan di kawasan adat, melakukan tindakan melukai tanah (tanah lah luko) membelah bukit (bumi lah koyak) memutus aliran sungai (tanjung lah putus) dan menebang pohon (ranting lah dipatah).
Untuk ‘merusak’ alam harus sesuai arahan adat. Apabila tidak dilakukan maka bencana akan turun. Sejauh ini sudah 4 orang pekerja meninggal dunia. Kearifan lokal itu dengan sirih pinang, untuk meminta kepada alam, untuk melakukan tindak tanduk tertentu.
“Kami memiliki kepercayaan kalau sembarangan mengelola alam, bencana pasti akan datang. Jadi agar anak cucu kami, yang tinggal dekat dengan pembangunan, harus aman dan selamat dari bencana,” kata Datuk Mukhri.
Untuk saat ini, denda yang dijatuhkan ke PLTA Batang Merangin adalah potong kerbau, beras 100 gantang dan lemak semanis. Setelah itu mereka penuhi, orang adat akan turun untuk meminta izin kepada ‘yang lain’ penunggu alam raya.
Banyak kearifan untuk berhubungan dengan alam, sehingga dilarang sembarangan merubah bentang alam seperti melukai atau mengeksploitasi tebing cae (tebing curam) luhah dalam (lembah dalam) imbo sako (hutan adat) dan bukik tinggai (bukit yang tinggi). Untuk melakukan itu, selaku pemilik kawasan adat Depati Muaro Langkap harus membuat ritual khusus.
“Kami percaya alam itu punya tuah (kekuatan) dan bisa membinasakan kita kalau salah mengelola bumi, bukit, hutan dan sungai,” kata Datuk.
Secara tidak langsung, keberadaan PLTA Batang Merangin telah berdampak kepada masyarakat adat. Sekarang itu, Muaro Langkap memiliki dua depati yaitu Mukhri Soni dan Hasrun. Sehingga anak jantan dan betino pun terbelah.
“Sekarang kami sudah terbelah dan terpecah. Kalau ada kematian atau pernikahan tidak saling tegur sapa. Bahkan tidak mau datang kalau ada undangan. Putus sudah silaturahim,” kata Datuk Mukhri Soni gamang. Yang menakutkan perpecahan ini akan turun ke anak-cucu, katanya.
Depati Rencong Telang, yang memiliki tanah adat di lokasi pembangunan PLTA juga sudah terbelah. Depati Rencong Telang, Marwazi Wahid dengan gelar Balinggo menuturkan perpecahan sesama masyarakat adat sudah sangat genting, kalau tidak putus. Perpecahan masyarakat adat Rencong Telang sangat kontras.
Dua depati itu, Marwazi Wahid menahkodai Rencong Telang, lainnya Rencong Telang Ujung Pagaruyung. Dengan kondisi ini, masyarakat adat yang awalnya guyub, menjadi terbelah. Masing-masing membuat garis pembatas yang tajam.
“Kami akhirnya masing-masing membuat jarak. Satu minang satu Kerinci. Tidak boleh menikah antara Rencong Telang dan Ujung Pagaruyung. Sekarang kuburan sudah dipindah, tidak satu lagi. Rumah adat masing-masing punya satu,” kata Wahid.
Sementara itu, Anak betino (perempuan) masyarakat adat Muaro Langkap, Evi Puspita, merasa sulit menempatkan diri di lingkungan masyarakat bahkan keluarga. Dia tidak menginginkan adanya permusuhan. Dari raut wajahnya, dia tampak gamang dengan masa depan anak-cucu.
“Saya sedih dan takut karena dibilang pengacau negeri oleh saudara sendiri. Padahal kita ini sedarah dan berasal dari yang satu. Saya ingin maju bersama-sama, saling mendukung dan harmonis seperti dulu. Jangan sampai tanah kita dikuasai orang. Anak cucu nantinya menumpang di tanah sendiri,” kata Puspita.
Dia mendukung perjuangan Datuk Mukhri untuk ‘merebut’ tanah adat, agar tidak menjadi hak milik perusahaan. Menurut Puspita apabila tanah adat dikuasai pihak lain, maka anak cucu akan menumpang di tanah sendiri.
Kesadaran untuk tidak melanggengkan perpecahan, kata Puspita harus meluas. Agar semakin banyak anak jantan dan betino yang sadar, untuk lebih memikirkan kepentingan bersama, dibanding kepentingan pribadi dan perusahaan.
Setelah satu dekade menolak, hampir seluruh masyarakat adat Muaro Langkap kini mendukung Pembangunan PLTA, milik anak usaha Kalla Grup. Terutama kelompok perempuan, berharap dalam memberikan kompensasi harus transparan dan adil. Sehingga tidak membuat masyarakat adat terbelah.
Ikan Semah Terancam Punah
Pembangunan ini berdampak pada kelangsungan hidup nelayan yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Aktivitas menutup sungai sementara membuat anak-anak sungai mengering dan berkurangnya sumber air. Dengan demikian, migrasi ikan semah dari dan menuju Danau Kerinci, menjadi terganggu.
Sekretaris Desa Batang Merangin, Yansori menuturkan dalam catatan pemerintah desa setelah perusahaan beroperasi membuat terowongan banyak sungai-sungai yang berada di kebun warga mengering. Kejadian ini diperparah saat pihak perusahaan mematikan aliran Sungai Batang Merangin untuk beberapa bulan.
“Mereka matikan sungai sementara, sebelum mereka membuat terowongan untuk mengalihkan aliran sungai. Tentu ini berdampak pada ikan semah, yang tidak bisa migrasi ke hulu (Danau Kerinci),” kata Yansori.
Dampak kekeringan sumber air, kata Yansori pihak perusahaan telah bertanggung jawab dengan membuat saluran air ke rumah warga dan kebun. Ada dua dusun yang terkena dampak kegiatan pembangunan PLTA, di antaranya Dusun Kampung Lereng dan Desa Sukaramai total penduduk di wilayah itu lebih dari 80 KK.
Banyak masyarakat yang hidup di aliran Sungai Batang Merangin masih mencari ikan semah. Risman nelayan dari Desa Pasar Tamiai menuturkan sebelum pembangunan PLTA air itu jernih. Sehingga mudah mendapatkan ikan. Dalam waktu setengah hari mencari ikan, dia telah mendapatkan 20-30 kilogram ikan. Namun kini dari pagi sampai sore hanya dapat setengah kilogram.

“Ikan semah itu mencari air yang jernih. Kalau airnya sudah keruh, dia tidak ada. Dia mabuk di air sungai yang keruh,” kata Risman.
Kepunahan ikan semah diperkuat dengan berkurangnya debit air yang berada di terjunan badan sungai setinggi 3 meter. Dengan adanya air terjun ini, ikan semah tidak berhasil melompak ke atas saat migrasi karena airnya sedikit. Menurut penelitian Tedjo Sukmono, ikan semah butuh migrasi ke Danau Kerinci untuk bertelur dan ke hilir sungai untuk pemijahan di batu-batu sungai.
Tedjo menuturkan untuk menghindari kepunahan ikan semah endemik, perusahaan harus membangun jembatan ikan. Tidak hanya itu, harus menjaga ekosistem sungai tetap alami, tidak melakukan tindakan, yang memperburuk kualitas air. “Jangan sampai airnya terganggu,” kata Tedjo Ahli Ikan Air Tawar Universitas Jambi.
Nelayan yang sudah gantung pancing ini berharap ikan semah tetap menjadi komoditas utama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini Risman memilih bertani, meskipun berharap ikan semah kembali seperti dulu. Dan dirinya kembali menjadi nelayan.
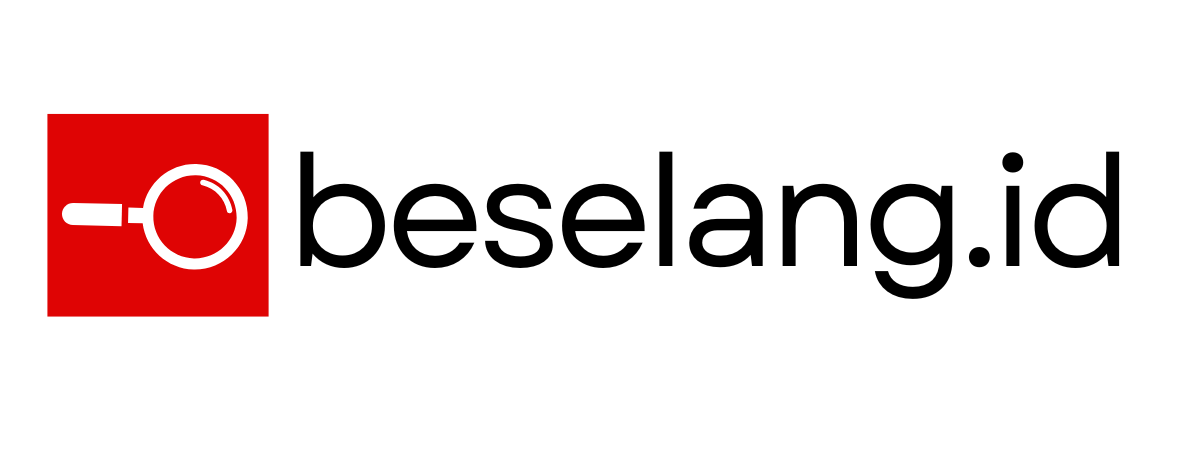









Leave feedback about this